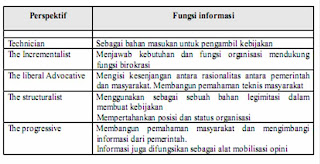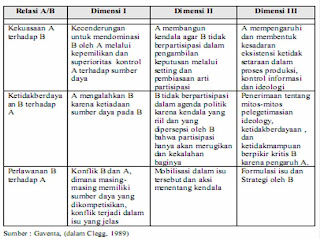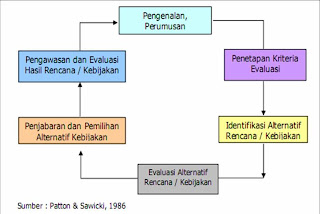Sejak dicanangkannya
kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu
mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi
sipil makin marak tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak
memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu
menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai dengan
pelayanan hak-hak sosial dasar.
Banyak cara
telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya
gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian
warga, mengangkat isu-isu populis. Pilihan advokasi dilakukan dalam
tiga model: (1) pendekatan diplomasi; (2) pengembangan wacana kritis;
sampai dengan (3) pengorganisasian masyarakat. Dalam rentang perubahan
pada babak awal reformasi, pilihan pengorganisasian masyarakat sering
ditempuh oleh para aktivis, sebagai bagian dari episode merintis pondasi
dan membangun tembok bagi demokrasi lokal, yang telah lama menjadi harapan
sejak reformasi dideklarasikan.
Sementara,
berkenaan dengan peran pemerintah daerah, sejumlah perubahan juga patut
disyukuri. Merujuk bermacam riset mengenai local governance
reform, telah memberikan informasi-informasi positif. Sekurang-kurangnya
pada aras formal kelembagaan, juga regulasi, telah banyak inisiatif-inisiatif
awal oleh pemerintah yang makin tumbuh. Hal itu dapat digolongkan sebagai
respon atas tuntutan perubahan yang dikawal para CSO (civil
society organisation), maupun sebentuk political
will yang lahir dari teknokratisasi pemimpin daerah. Dapat disebutkan
misalnya: terbentuknya peraturan-peraturan daerah (Perda) berkaitan
dengan partisipasi sipil dalam kebijakan publik, pembaharuan tata kelola
perijinan dan pelayanan masyarakat, transparansi dan partisipasi dalam
perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta yang paling aktual adalah
inisiatif perubahan anggaran yang berpihak pada kaum miskin atau yang
dikenal dengan reformasi social policy (pendidikan dan kesehatan).
Meskipun pada
aras masyarakat sipil dan negara telah dicapai kemajuan positif, banyak
catatan penting di seputar kendala tak bisa dielakkan. Perubahan yang
berlangsung sejauh ini, tidak berarti secara otomatis berujung pada
implementasi yang konsisten sesuai koridor normatif. Perubahan tata
kelembagaan yang berlangsung secara radikal, khususnya di bidang politik
formal, dibarengi sejumlah bukti keadaan sosial ekonomi masyarakat yang
menunjukkan fakta berlawanan. Jerit keluh warga terkait problem-problem
sosial ekonomi, masih terus terdengar. Bahkan makin keras. Demokrasi
politik belum membuahkan kesejahteraan.
Berbagai langkah
politik warga membendung dan mengatasi segala macam masalah itu, memang
bukan pekerjaan mudah. Pengalaman pahit makin merisaukan masyarakat,
terutama banyaknya pengingkaran agenda reformasi. Kerisauan dan sinisme
makin mencuat, menyaksikan berbagai jebakan pragmatisme yang selalu
menghantui irama dan dinamika lokal. Kemerosotan kepercayaan makin berlangsung
saat reproduksi ketegangan antar kelompok sipil dalam advokasi kebijakan
makin menebal, yang seringkali diiringi sikap dan tindakan yang saling
berbenturan. Propaganda buruk antar aktivis muncul, meski hanya berkutat
pada perbedaan pilihan strategi, tanpa ditopang komunikasi antar mereka.
Perselisihan tanpa kompromi dan negosiasi, justru mengurangi energi
bagi bangunan konsistensi kesadaran dalam perjuangan.
Meningkatnya
derajat partisipasi formal, yang didorong dalam sketsa demokratisasi
lokal, nampaknya belum berkorelasi positif dengan derajat perubahan
kebijakan secara nyata. Bahkan partisipasi itu, seringkali terjebak
dalam formalisasi. Menyangkut perencanaan pembangunan dan penganggaran,
sesungguhnya secara normatif telah tertuang beberapa regulasi. Sebut
saja misalnya, berkenaaan dengan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang), yang mensyaratkan pendekatan partisipasi, telah diatur
melalui UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan daerah.
Partisipasi
dalam perencanaan pembangunan, yang diatur dalam dua regulasi tersebut,
ternyata membentur proses penganggaran daerah. Proses penganggaran ini
mengikuti regulasi yang khusus mengaturnya, yaitu UU No 17/2003 tentang
Keuangan Negara dan UU No 33/2004 tentang perimbangan dana pemerintah
pusat dan daerah. Meski kehendak regulasi berupaya mengintegrasikan
proses perencanaan dan penganggaran, namun dalam praktiknya yang sering
terjadi di banyak daerah adalah disconnection antara hasil Musrenbang
kabupaten dengan posting alokasi belanja anggaran. Hasil Musrenbang
dalam bentuk daftar skala prioritas (DSP), tidak dijadikan referensi
nyata dalam posting alokasi anggaran oleh tim anggaran pemerintah daerah
(TAPD) dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Karena itu, bisa disadari
bahwa anggaran daerah cenderung disusun secara oligarkis oleh eksekutif
dan legislatif, sehingga tidak bisa disentuh (untouchable) oleh
partisipasi masyarakat.
Padahal, Permendagri
nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui akses informasi yang seluas-luasnya tentang
keuangan daerah. Dalam cara pandang kritis, terjadinya elitisasi dan
oligarki proses perencanaan dan penganggaran, berakibat pada kecenderungan
formalisasi Musrenbang yang tidak bisa dijadikan tolok ukur perencanaan
yang partisipatif dan transparan. Wajar saja, jika akhirnya output Musrenbang
dan penganggaran, dalam bentuk APBD, tidak sesuai harapan. Hal ini biasanya
tercermin dari, besaran partispasi warga dalam Musrenbang tidak berkorelasi
positif atas alokasi anggaran yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat.
Apalagi, di
sejumlah kasus menunjukkan modus-modus perilaku aktor-aktor yang memanfaatkan
secara informal proses kebijakan perencanaan maupun penganggaran, yang
menerobos jalur formal (prosedural). Tidak mengherankan, jika akhirnya
arena penganggaran memperlihatkan dua gerak sirkuit: arus formal dan
informal dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan dan penganggaran,
yang berujung pada abainya kepentingan masyarakat luas, apalagi kelompok
marginal. Kontestasi formal seringkali berbeda dengan geliat penetrasi
aktor-aktor informal, termasuk jaringan agencies dalam institusi
pengambil kebijakan. Disanalah, tidak jarang senantiasa muncul ”penumpang
gelap” kebijakan, yang mendistorsi kebijakan.
Skema perencanaan
dan penganggaran semestinya mensyaratkan perpaduan antara pendekatan
teknokrasi, politik dan partisipasi. Kaitan antar pendekatan tersebut
merupakan konstruksi demokratisasi kebijakan. Namun faktanya, kecenderungan
modus perencanaan dan penganggaran daerah masih bersifat terlalu teknokratis-politis,
tidak diimbangi dengan aspek partisipasi yang nyata. Sebagai ukuran,
bahwa di setiap hasil Musrenbang yang diolah pada tingkat SKPD, selalu
mengalami pemangkasan di lintasan eksekutif. Apalagi, pada fase penganggaran,
senantiasa absen dari pantauan dan keterlibatan warga. Tahap krusial
yang perlu diperhatikan, karena sekaligus menjadi titik strategis penentu
perencanaan, tidak lain ada pada tahap perumusan program/kegiatan SKPD
yang dikoordinasi Bappeda.
Proses dan
rute dari bawah, sesungguhnya sangat bergantung bagaimana pembahasan
masuk dalam sistematisasi dan rasionalisasi dalam kacamata SKPD yang
didalamnya terjadi “interaksi” sekaligus pertarungan antar sektoral.
Arena ini, memang sebagian besar memiliki modus yang sama mengenai kecenderungan
para kepala dinas memperjuangkan segala usulan masing-masing instansi
berbasis keinginannya. Silang kepentingan dengan nalar teknokratik,
berproses dengan (cenderung) mengabaikan segala dokumen usulan dari
hasil Musrenbang. Bahkan tragisnya, produk perencanaan teknokratik tersebut
meninggalkan koherensinya dengan RPJMD, Renstra, maupun Renja SKPD.
Hal itu bisa terjadi karena mekanisme perencanaan pembangunan telah
“terbakukan dalam sangkar birokratik”.
Perangkat kelembagaan
dan mekanisme perencanaan jika sudah memasuki area kabupaten, daftar
usulan dari hasil Musrenbang mengalami penyusutan secara sistematik,
dengan tergantikan oleh bermacam skema yang berasal dari dinas-dinas
(SKPD). Hal semacam ini memperlihatkan terjadinya gap (kesenjangan),
antara model perencanaan dari bawah berbasis spasial (desa), yang menunjukkan
pendekatan partisipasi, berhadapan dengan model perencanaan berbasis
sektoral (daerah/kabupaten), yang mencerminkan teknokratisasi. Salah
satu akar penyebab kesenjangan, sebagaimana disinyalemen banyak kalangan,
bahwa jika perencanaan desa (dari bawah) itu masih melekat dalam perencanaan
daerah, sebagaimana diatur dalam tata kelembagaan Musrenbang, kemungkinan
berlanjutnya dominasi kabupaten akan terus berlangsung. Secara hipotetis
dapat dikatakan, set up tata kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah, senantiasa menjadi perangkap formalisasi partisipasi dan hanya
memperkuat dominasi SKPD.
Secara teoritik,
anggaran belanja daerah merupakan instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan
roda kekuasaannya. Dalam skema kebijakan, keputusan alokasi sumber daya
untuk berbagai keperluan berupa pengeluaran setiap tahunnya, tercermin
pada APBD. Dalam prakteknya, anggaran belanja daerah tak terlepas dari
sejumlah kepentingan yang harus diakomodasi, sekaligus menjadi mediasi
berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks demikian, kebutuhan atau
kepentingan itu seringkali memiliki bobot prioritas yang relatif sama.
Dari sanalah diperlukan pilihan-pilihan memutuskan mana yang akan didanai
terlebih dahulu. Tidak heran jika atas pertimbangan itu pada akhirnya
berbagai pihak dan kelompok kepentingan akan berebut pengaruh di dalam
memutuskan alokasi anggaran belanja daerah.
Anggaran belanja
daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah.
Dalam perspektif mikro, kebijakan anggaran belanja daerah adalah merupakan
keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.
Sebagai keputusan politik, kebijakan anggaran belanja daerah sering
melalui proses politik yang panjang dan kompleks. Prosesnya meliputi
tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang
atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, baik sebagai perencana, pelaksana
maupun penerima manfaat kebijakan anggaran belanja daerah. Sementara
dalam khasanah makro tata pemerintahan demokrasi, kebijakan anggaran
belanja daerah merupakan mandat politik warga (citizen political
mandate) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga
pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas
pengelolaan anggaran. Sifat otoritatif pemerintah demikian tentu hanya
berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu melaksanakan alokasi atau
distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga.
Kombinasi dua
perspektif setidaknya telah terefleksikan pada muatan Undang-undang
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pada Pasal 3 dinyatakan
bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya, selain proses kebijakan
penganggaran mengacu kepada prinsip-prinsip teknokratis, lebih dari
itu yang patut digaris bawahi adalah adanya proses politik dan partisipasi
warga.
Dalam pengertian
yang luas, anggaran memiliki fungsi distributif, yang diartikan bahwa
suatu anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai
fungsi alokasi sumberdaya, anggaran harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan efektivitas
dan efisiensi perekonomian. Untuk itulah, penyusunan anggaran harus
mempergunakan prioritas kebutuhan dasar bagi masyarakat, apa yang akan
dipenuhi, memperkirakan sumber daya yang dimiliki pada tahun yang akan
datang, pelayanan atau pembangunan apa yang akan diberikan pemerintah
untuk satu tahun ke depan.
Anggaran belanja
daerah mempunyai beberapa karakteristik yang membuat anggaran itu sarat
dengan masalah-masalah politik. Pemerintah daerah menyusun anggaran
itu secara teknis dengan kriteria efesiensi dan profesional. Biasanya
pejabat-pejabat penyusun itu mempunyai pendidikan yang khusus mendalami
masalah-masalah anggaran, tetapi kadang-kadang perhitungan-perhitungan
yang telah disusun secara teknis dan profesional itu sulit disajikan
secara rasional, karena adanya intervensi dari unsur-unsur politik.
Di sini berhadapan antara penyusun anggaran yang profesional dengan
para politisi yang bekerja dengan pertimbangan politik. Dengan kata
lain, terdapat batasan antara keputusan-keputusan yang bersifat teknis
dari para penyusun anggaran, dan bersifat politis dari para politisi
atau anggota legislatif.
Diantara anggota
legislatif yang mewakili rakyat itu, sering terjadi konflik diantara
mereka sendiri. Jadi konflik bukan terjadi antara anggota legislatif
dan penyusun anggaran atau pemerintah saja, tetapi juga dapat terjadi
dikalangan dewan legislatif. Anggota legislatif itu mewakili kelompok-kelompok
masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, antara lain
kelompok-kelompok ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Dengan demikian dikalangan
legislatif itu, tidak heran apabila disatu pihak memperjuangkan anggaran
untuk golongan pengusaha yang sudah mapan.
Dimensi politik
dan kepentingan dalam perumusan kebijakan publik merupakan sebuah hal
yang lazim terjadi di Indonesia termasuk dominasi elite kekuasaan di
dalam mempengaruhi perumusan kebijakan. Pengaruh politik dalam anggaran
bukan hanya pada penyusunannya, tetapi juga pada prosesnya. Proses anggaran
yang dimaksud adalah dari mulai tingkat usulan sampai ke pelaksanaan
dan penilaian. Pada proses inilah unsur-unsur politik itu banyak bermain
atau berperan. Pada akhirnya, kebijakan banyak dianggap sebagai sebuah
upaya mempertahankan kekuasaan.
Formulasi kebijakan
perencanaan merefleksikan sebuah gugatan terhadap peran elit kekuasaan
yang memegang kendali utama dalam proses perumusan kebijakan yang akan
menentukan masa depan banyak pihak; bukan hanya negara/daerah sebagai
sesuatu yang pasif namun, masyarakat sebagai sesuatu yang aktif termasuk
masa depan negara/daerah.
Dalam perspektif produk kebijakan, perencanaan daerah merefleksikan sebuah gugatan terhadap sisi kelayakan dan rasionalitas atas substansi kebijakan perencanaan. Berangkat dari fenomena yang telah digambarkan, dengan segenap kekuatan pada derajat analisis pengalaman, penelitian formulasi kebijakan berusaha menginterpretasikan persoalan pada proses perencanaan (formulasi) dan kelayakan substansi perencanaan (produk) dari kebijakan perencanaan. Tentu bukan bermaksud replikasi, atau universalisasi. Segala keterbatasan yang dikandungnya, memberi harapan pula untuk kritik dan input, agar setiap upaya perubahan pada level proses selalu bermakna, andai belum menghadirkan perubahan langsung dalam waktu pendek. Pengetahuan dengan basis pengalaman yang terakumulasi dari manapun, semoga kian mencerahkan sesama.